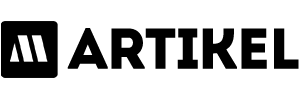DOSEN Dosen dan peneliti Universitas Islam Indonesia (UII), Listya Endang Artiani, menyoroti fenomena “Rojali” (rombongan jarang beli), “Rohana” (rombongan hanya nanya), dan “Robeli” (rombongan benar-benar beli) yang viral di media sosial. Menurutnya, fenomena ini membuka tabir realitas sosial-ekonomi Indonesia yang lebih kompleks.
“Di balik humor dan meme yang beredar, tersimpan ironi mendalam: keramaian pusat perbelanjaan tidak selalu mencerminkan kemakmuran. Justru, bisa jadi itu adalah indikasi ketimpangan daya beli dan rapuhnya ekonomi kelas menengah,” ungkap Listya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 4 Agustus 2025.
Ketimpangan Daya Beli dan Ilusi Kelas Menengah dalam Pusaran Rojali dan Rohana
Listya, yang merupakan pengajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, menjelaskan bahwa mal saat ini telah bertransformasi lebih dari sekadar pusat perbelanjaan. Mal menjelma menjadi ruang sosial-ekonomi multifungsi. Di sana, orang tidak hanya berbelanja barang, tetapi juga “membeli” pengalaman, membangun citra diri, dan merasakan modernitas.
Banyak orang, lanjut Listya, mengadopsi gaya hidup kelas atas sebagai representasi identitas, bukan karena kemampuan finansial yang sebenarnya. Perilaku konsumtif yang didorong oleh aspirasi sosial, bukan kemampuan riil, semakin diperkuat oleh media sosial yang mempromosikan budaya konsumsi pertunjukan (performative consumption).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya sekitar 20-30% penduduk Indonesia yang masuk kategori kelas menengah berdasarkan indikator pengeluaran riil. Namun, survei persepsi dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat mengidentifikasi diri sebagai kelas menengah.
Kesenjangan ini, menurut Listya, memunculkan “ilusi kelas menengah” (middle-class illusion). Kondisi ini terjadi ketika persepsi masyarakat tentang kelas sosial mereka tidak sejalan dengan pendapatan dan daya beli yang sebenarnya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa mal tetap ramai dikunjungi, meskipun hanya sebagian kecil pengunjung yang benar-benar melakukan pembelian.
Listya menambahkan bahwa kehadiran Rojali dan Rohana di mal bukan semata-mata karena pilihan, melainkan karena terbatasnya alternatif ruang publik yang gratis, nyaman, dan inklusif di perkotaan. Mal menjadi semacam “ruang publik” pengganti, di mana orang bisa merasa menjadi bagian dari modernitas dan komunitas, meskipun hanya dengan berjalan-jalan atau berfoto tanpa harus berbelanja.
“Kondisi ini juga mengindikasikan kelemahan dalam desain kebijakan makroekonomi yang terlalu fokus pada stimulus konsumsi jangka pendek,” tegas pengajar Jurusan Ekonomi ini.
Menurut Listya, program-program seperti festival belanja, diskon besar-besaran, atau subsidi harga memang mampu memicu lonjakan konsumsi sesaat. Namun, kebijakan tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan ketahanan ekonomi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi domestik yang sehat dan berkelanjutan hanya akan terwujud jika fondasi pendapatan masyarakat diperkuat.
“Hal ini termasuk melalui kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, jaminan sosial yang komprehensif, dan pengendalian harga kebutuhan pokok,” jelasnya.
Oleh karena itu, Listya menekankan bahwa fenomena Rojali dan Rohana harus dipahami sebagai gejala struktural, bukan sekadar lelucon budaya digital. Fenomena ini adalah cerminan dari ekonomi aspiratif yang rapuh, dari kelas menengah yang hidup di antara mimpi dan kenyataan.
“Tugas pemerintah, akademisi, dan pelaku industri adalah memahami dinamika ini secara komprehensif dan menyusun intervensi kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat konsumsi yang lebih berdaya, setara, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pilihan Editor: Asal Usul Rojali, Rohana, dan Robeli: Antara Lelucon Pop dan Gejala Sosial