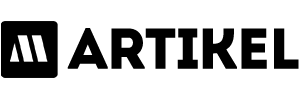FENOMENA menurunnya daya beli masyarakat Indonesia, terutama yang terlihat dari kebiasaan pengunjung mal, telah memunculkan istilah unik seperti Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya). Meskipun terdengar jenaka, fenomena ini sejatinya menjadi indikator penting kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak prima, memicu pertanyaan mendalam tentang dampaknya terhadap industri ritel dan ekonomi mal.
Menurut Listya Endang Artiani, seorang Dosen dan Peneliti dari Universitas Islam Indonesia (UII), istilah Rojali dan Rohana bukanlah sekadar lelucon. Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai “teks sosial” yang secara gamblang mencerminkan transformasi gaya hidup kelas menengah perkotaan serta pergeseran fungsi mal itu sendiri. Mal, yang dulunya hanya dipandang sebagai pusat transaksi rasional, kini telah berkembang menjadi ruang konsumsi yang memiliki dimensi emosional, simbolik, bahkan politis.
“Mal saat ini telah melampaui perannya sebagai pusat perdagangan. Mal, telah menjelma menjadi ruang sosial-ekonomi multifungsi, tempat di mana orang tidak hanya membeli barang, tetapi juga membeli suasana, membangun citra diri, bahkan membeli rasa berada di tengah modernitas,” jelas Listya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 04 Agustus 2025.
Dampak Fenomena Rojali dan Rohana terhadap Ekonomi Mal dan Strategi Retail
Listya, yang juga mengajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, mengakui bahwa fenomena Rojali dan Rohana—konsumen yang berkunjung ke mal tanpa niat belanja—sering kali dianggap sebagai beban ekonomi bagi pelaku bisnis ritel. Mereka tidak langsung menghasilkan transaksi, tidak meningkatkan omset, dan terkadang hanya dipandang sekadar “mengisi bangku kosong dan pendingin ruangan.”
Namun, pandangan ini dinilai terlalu sederhana dan gagal menangkap dinamika ekonomi kontemporer, terutama dalam era yang didominasi oleh experience economy dan ekonomi atensi. Dalam lanskap konsumsi modern, kehadiran fisik dan keterlibatan sosial justru merupakan aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis tersendiri. Listya menjelaskan bahwa Rojali dan Rohana, meski tidak membayar dengan uang, mereka berkontribusi dengan waktu, perhatian, bahkan melalui user-generated content di media sosial. Keramaian di mal, bahkan jika diisi oleh mereka yang hanya berjalan-jalan, menciptakan ilusi “kesuksesan sosial” yang pada gilirannya dapat membentuk ekspektasi positif bagi pengunjung baru.
“Ini sesuai dengan prinsip network externalities dalam teori ekonomi digital, di mana nilai suatu layanan meningkat seiring dengan banyaknya partisipan, walau tidak semua melakukan transaksi langsung. Efek ini juga erat dengan prinsip bandwagon effect dalam behavioral economics, di mana keputusan individu sering dipengaruhi oleh ekspektasi dan perilaku kolektif,” imbuh Listya.
Meskipun demikian, tantangan bagi pelaku ritel tetaplah nyata. Pengukuran kinerja toko masih didominasi oleh metrik konvensional seperti conversion rate, average basket size, dan sales per square meter. Ketika jumlah pengunjung meningkat tetapi tingkat transaksi stagnan, muncul apa yang disebut sebagai retail paradox: keramaian tanpa profit. Kondisi ini menekan return on investment (ROI) bagi tenant, terutama mengingat tingginya biaya sewa dan operasional di pusat perbelanjaan modern. Untuk menyiasati hal ini, banyak pelaku ritel mengadopsi pendekatan retailtainment—gabungan antara ritel dan hiburan—guna menciptakan nilai tambah yang tidak semata-mata berorientasi pada transaksi, melainkan pada pengalaman dan emosi.
“Mal tidak lagi hanya menjual barang, tetapi menjual suasana, cerita, dan citra diri. Fenomena ini selaras dengan argumen Joseph Pine dan James Gilmore (1998) dalam The Experience Economy, yang menyatakan bahwa lapisan tertinggi dari nilai ekonomi bukanlah produk atau jasa, melainkan pengalaman personal yang bermakna,” kata pengajar Jurusan Ekonomi ini.
Lebih lanjut, Listya memaparkan implementasi konkret dari transformasi mal ini terlihat dari perubahan format toko: toko buku menjadi ruang komunitas, gerai kopi menjadi galeri mikro, hingga fashion store yang menyisipkan ruang swafoto dan event pop-up. Beberapa pusat perbelanjaan bahkan mulai menambahkan elemen co-working space, urban garden, atau area bermain interaktif sebagai bentuk strategi place-making yang lebih bersifat partisipatif.
Namun, transformasi ini juga menyimpan ironi. Di balik narasi inklusivitas dan pengalaman, tetap ada preferensi kuat terhadap konsumen “Robeli” atau rombongan benar-benar beli, yang datang dengan daya beli tinggi dan niat belanja jelas. Logika pasar masih mendorong seleksi berdasarkan kontribusi ekonomi langsung. Akibatnya, pelaku UMKM dan tenant lokal yang tidak mampu bersaing dalam model ekonomi berbasis volume dan margin tinggi berisiko terpinggirkan, memperkuat ketimpangan struktural antara pelaku bisnis besar dan kecil dalam satu ekosistem konsumsi yang tampak terbuka namun sesungguhnya hierarkis.
Oleh karena itu, Listya menekankan pentingnya inovasi kebijakan dalam manajemen mal dan tata kelola ritel. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penggunaan prinsip inclusive economy, yang menekankan distribusi nilai dan akses ekonomi yang lebih merata. Pengelola mal dapat merancang skema sewa berbasis performa sosial, insentif bagi tenant komunitas, atau alokasi zona “non-komersial” yang memungkinkan interaksi warga tanpa tekanan konsumsi. Model semacam ini tidak hanya berkelanjutan secara sosial, tetapi juga memperluas makna dari value proposition mal sebagai institusi urban yang adaptif dan relevan di tengah krisis ekonomi maupun perubahan perilaku konsumen.
“Dengan kata lain, kehadiran Rojali dan Rohana adalah cermin. Mereka memaksa industri ritel untuk bertanya: untuk siapa ruang-ruang konsumsi ini diciptakan, dan nilai apa yang sebetulnya sedang dijual? Pertanyaan ini tidak hanya bersifat ekonomis, tapi juga etis dan jawabannya akan menentukan arah masa depan ritel dan ruang publik kita,” tutup Listya.